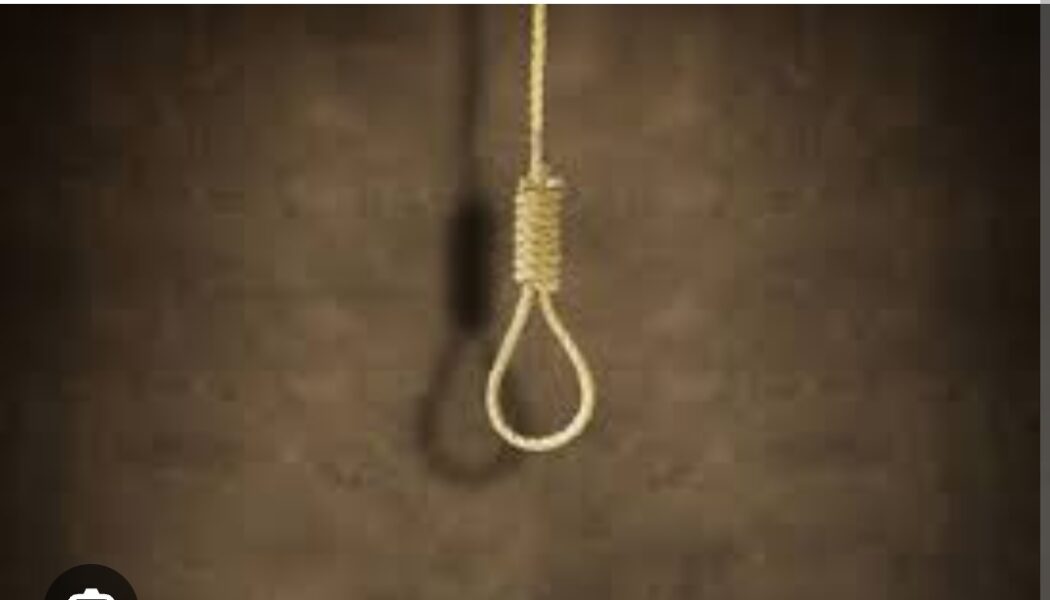Oleh : Umnia labeb
Anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI B. anyumas
Peringatan hari Kartini 2021 kali ini diantaranya diwarnai dengan keprihatinan akan kenaikan angka pernikahan anak di Indonesia, yang terutama terjadi pada anak perempuan.
Di Banyumas misalnya, sebuah media mengungkapkan data pernikahan anak pada Pengadilan Agama Banyumas mengalami peningkatan pesat.
Pada tahun 2019 jumlah total pemohon dispensasi kawin hanya 114. Sedangkan pada 2020 angkanya meroket sampai 234 pemohon.
Menariknya menurut panitera pengadilan Agama kabupaten Banyumas berdasarkan Fakta di persidangan, menunjukan faktor budaya menikahkan anak perempuan di bawah umur masih mendominasi, terutama di wilayah pedesaan atau pelosok, selain faktor lainnya seperti ekonomi, salah pergaulan, pengaruh media sosial dan faktor lainya.
Pernikahan dini bagaimanapun adalah preseden buruk bagi masa depan bangsa. Pelaku pernikahan dini niscaya tak memahami benar pikiran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah dikemukakan lebih dari seabad lampau. Pada eranya, Kartini baru naik ke pelaminan pada usia 24 tahun.
Di masa di mana hampir semua perempuan di eranya telah dinikahkan begitu memasuki usia belasan tahun. Tidak hanya itu, meski lahir dan besar di lingkungan budaya Jawa yang menganut prinsip ‘banyak anak, banyak rezeki’, perempuan kelahiran Jepara, 21 April 1879, itu menentangnya dengan keras.
Selain sangat memperhatikan faktor kesehatan perempuan atau si ibu yang mengandung dan melahirkan, Kartini concern terhadap masa depan anak-anak. Tentu, realitas hari ini berbanding terbalik dengan cita luhur RA Kartini yang dengan lantang di masa penjajahan telah bersuara keras tentang hak anak, hak pendidikan khususnya bagi perempuan.
Perempuan, Pernikahan dini dan Belenggu Budaya
Pernikahan dini atau pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi pada usia anak. Ketentuan batas usia minimal pernikahan telah diatur melalui UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan, dengan demikian, jika dilakukan di bawah usia 19 tahun masuk dalam kategori dini atau pernikahan anak.
Pada tahun 2018 Indonesia berada pada nomor urut kedua negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di ASEAN dan menempatkan Indonesia pada 10 (sepuluh) negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Pandemi yang melanda dunia turut berpengaruh pada peningkatan pernikahan anak di berbagai daerah yang berpotensi melejitkan angka pernikahan anak di Indonesia di tataran dunia.
Mirisnya, dalam angka-angka tersebut anak perempuanlah yang banyak menjadi korban. Dari laporan penelitian tim UI bekerjasama dengan UNICEF dan BPS menyebutkan pernikahan anak perempuan adalah 1 dari 10 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun sementara anak laki-laki menunjukkan 1 dari 100 anak laki-laki menikah di bawah usia 18 tahun.
Fakta di atas menunjukan kuatnya struktur patriarkhi di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam beberapa aspek, perempuan menjadi korban termasuk dalam pernikahan anak. Pada masyarakat dengan struktur dan kultur patriarkhi, perempuan masih dianggap sekedar sebagai “konco wingking”, yang darma bakti hidupnya sebatas “sumur, dapur dan Kasur”.
Alimatul Qibtiyah dalam penelitianya tentang feminisme di Indonesia menemukan adanya konstruk budaya pada perempuan Jawa yang oleh kulturnya dikonstruksikan hanya memiliki kekuatan dalam sektor informal yaitu, manak, macak dan masak (beranak, memasak dan berdandan). Argumen kultural ini menempatkan perempuan sebagai objek dalam budaya yang berakibat masyarakat memandang pendidikan bagi anak perempuan sekedarnya saja dan bukan kebutuhan elementer bagi anak.
Anak perempuan juga acap kali dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga melepasnya dalam pernikahan adalah bagian dari mengurangi beban ekonomi keluarga.
Jika dalam prespektif perlindungan anak, pernikahan anak secara umum adalah pelanggaran terhadap setidaknya 5 (lima) hak anak yaitu : Pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, hak untuk berpikir dan berekspresi. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi. Kelima, hak perlindungan.
Maka pada anak perempuan dampak itu menjadi berlipat, bukan hanya terampasnya hak. Anak perempuan harus mengalami hamil, melahirkan, nifas dan menyusui yang membutuhkan waktu yang terbilang tahunan. Hal ini membawa konsekuensi anak perempuan yang menikah dini mengalami putus sekolah, sementara nak laki-laki yang menikah dini masih dapat melanjutkan pendidikan. Tugas reproduksi yang diemban anak perempuan akibat pernikahan dininya, seringkali disertasi berbagai konsekuensi biologis dari rasa sakit, tidak nyaman hingga ancaman kematian.
Tugas reproduksi ini adalah khas perempuan, yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Dalam pengasuhan, konstruk budaya masih memandang pengasuhan sebagai kewajiban mutlak perempuan, sehingga dalam usia yang belum matang secara psikis tersebut anak perempuan yang menikah dini menanggung lebih banyak beban psikologis yang seringkali menimbulkan depresi.
Berbeda dengan anak laki-laki meski ia melakukan pernikahan usia muda, ia masih bisa bermain, bersekolah, menyalurkan hobi dan lain sebagainya karena tidak ada tugas reproduksi yang berjangka tahunan sebagaimana anak perempuan. Anak perempuan yang melakukan pernikahan dini juga rentan mengalami berbagai kekerasan yang diakibatkan dari stigma tentang kedudukan perempuan yang ada dalam konstruk budaya masyarakat.
Mencegah Pernikahan Dini : Jalan Panjang Kartini
Tampaknya, di era milenial ini jalan panjang Kartini meretas kemandirian perempuan dan mengangkat harkat dan derajat perempuan masih lah panjang ke depan. Jalan panjang kartini dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia telah dimulainya sejak masa kolonial Belanda, saat dimana perempuan Indonesia kebanyakan masih dinina bobokan oleh rezim kolonialis, struktur sosial berkasta dan kultur patriarkhis.
Kasta sosial saat itu menunjukkan bahwa perempuan harus berada di bawah pria. Perempuan juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dalam hal pendidikan bahkan memilih pasangan hidupnya. Boleh dikata semua perilaku wanita sudah diatur sedemikian rupa dan tidak boleh dilanggar. Namun, Kartini memiliki pemikiran yang berbeda. Beliau merasa bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan para pria. Itulah yang mendasari keinginanan Kartini untuk memajukan perempuan bangsa Indonesia saat itu.
Kartini sendiri hanya diizinkan sekolah sampai tamat E.L.S. (Europese Lagere School) atau setara dengan sekolah dasar. Setelah tamat sekolah, Kartini harus menjalani masa pingitan hingga saatnya tiba untuk menikah. Ini merupakan adat-istiadat yang berlaku saat itu. Ketertarikannya dalam membaca, akhirnya membuat Kartini memiliki wawasan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Dari sinilah, Kartini mulai menyadari bahwa wanita sebangsanya sangat tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa lain, terutama Eropa. Sejak saat itu, beliau mulai memberikan perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita dengan membandingkan antara wanita Eropa dan pribumi. Selain itu, Kartini juga menaruh perhatian pada masalah sosial.
Menurutnya, seorang wanita juga perlu memperoleh hak yang sama dengan pria perihal kebebasan, otonomi dan juga kesetaraan hukum.
Jalan panjang Kartini semestinya kita makmumi, membawa perempuan bangsa ini meraih harkat dan martabatnya. Pernikahan dini adalah jalan pintas yang memotong perjuangan Kartini dan perjuangan para pahlawan bangsa menuju bangsa Indonesia yang berkadaban, maju dan kompetitif dengan bangsa lain. Di era teknologi informasi yang sudah melesat pada teknologi 5.0, Indonesia masih gagap menyambut 4.0 sebagai barang baru.
Bagaimana bangsa ini akan berkompetisi jika penerima tongkat estafet bangsa sudah terjebak dalam pernikahan anak yang merampas banyak masa tumbuh kembangnya. Anak sebagai asset bangsa, dan perempuan sebagai bagian dari komponen bangsa. Tidak akan tegak bangsa ini berdiri tanpa kemajuan dan kemandirian mereka.
Perlu kerja keras bersama, berada di jalan perjuangan RA Kartini, dengan permasalah yang sama dalam bentuk dan manifestasi problematika yang berbeda. Mencegah Pernikahan dini membutuhkan sinergi. Tidak cukup menjadi jargon, tetapi harus menjadi prespektif bersama. Jika budaya masih menjadi faktor dominan, perlu pemerintah berjalan tidak sebatas regulasi. Mendidik warga masyarakatnya adalah pekerjaan panjang yang harus terus ditempuh.
Bergandeng tangan dengan para agamawan, akademisi, praktisi, aktivis kemanusiaan hingga simpul-simpul di masyarakat di bawah. Kurikulum pendidikan pun harus bisa menjangkau pendidikan hak anak, hingga anak memiliki khazanah tentang pembangunan jati diri dan masa depan bangsa. Pendidikan hak reproduksi pada anak sejak dini pun penting disampaikan.
Di aras agama, tafsir baru atas fikih pernikahan harus bisa membawa pemahaman pada tujuan maqhasid syariah agar pernikahan anak dapat dicegah. Kampanye pencegahan pernikahan anak adalah tugas kita bersama. Dan, Kartini telah memulainya sekian abad lampau. Akankah kesia-siaan suara kartini jika kita abai terhadap fenomena ini? Tidak, saatnya bersama katakana : stop pernikahan anak.(#)